Weekend lalu, sebuah bis bertingkat dua membawa kami dari Bayreuth ke Berlin. Matahari akhir musim semi masih bersinar pukul 19:00, waktu aku masuk ke Hotel Altberlin dengan suasana klasik (bergaya masa antara dua perang dunia) di Potsdamer Platz. Di peta, hotel yang aku pilih itu berada tak jauh dari Berlin Philharmonie. Jadi kuputuskan untuk menikmati waktu sebelum matahari terbenam untuk ke Philharmonie. Tapi ternyata cukup jalan 10 menit saja untuk sampai. Di sana, aku memilah2 program yang bisa ditampilkan, dan memilih orkestra hari berikutnya. Maka acara menunggu matahari terbenam sore itu dilanjutkan di sekitar Potsdamer Platz hingga Branderburg Tor yang sering dianggap landmark Berlin itu.

Hari berikutnya, kami datang lagi. Kali ini naik bis menembus hujan rintik. Malam ini, Berliner Philharmoniker akan dipimpin oleh Herbert Blomstedt memainkan Missa Solemnis dari Beethoven. Sebagai choir adalah Bayerischer Rundfunk.

Mungkin bayangan kita atas Beethoven adalah image dari lukisan potret Beethoven oleh Joseph Karl Stieler. Dalam lukisan itu, Beethoven mengenakan baju putih, syal merah, dan jaket atau jubah hitam; serta sedang menulis komposisi Missa Solemnis. Komposisi ini adalah satu dari beberapa karya yang dianggap karya puncak dari Beethoven. Ia ditulis pada masa yang sama dengan Simfoni Kesembilan. Namun, tak seperti sembilan simfoni Beethoven, karya ini tak terlalu populer di kalangan publik.
Saat menulis karya ini, Beethoven sedang dalam masa krisis. Ketuliannya mengganggu aktivitasnya menyusun komposisi musik, sekaligus membuatnya makin terisolasi dari masyarakat. Pada masa ini, ia menyusun String Quarter terakhir, Simfoni Kesembilan, dan Missa Solemnis.

Missa Solemnis juga terinspirasi karya-karya para pendahulu, seperti fugue dan beberapa gaya Palestrina. Namun tentu warna yang dominan adalah warna klasik khas Beethoven yang mulai mengarah ke gaya romantik. Vokalnya konon masih jadi tantangan bahkan bagi solois dan choir masa kini. Dari segi ide, mungkin memang ada kaitan antara melankoli Beethoven masa itu dengan keinginannya untuk lebih dekat pada Tuhan. Namun yang terdengar justru adalah kedalaman dan variasi yang luar biasa dari pikiran dan perasaan Beethoven sendiri. Strukturnya, tentu berbeda dengan simfoni-simfoni Beethoven. Keterasingan struktur ini (buat aku), justru menambah misteri karya yang menurut penilaian Beethoven sendiri adalah komposisinya yang paling agung. Kata-katanya, hmmm, aku bahkan belum tahu ini bahasa Jerman atau Latin. Belum bisa dua-duanya sih.
Lebih dari 10 tahun sebelumnya memang aku pernah juga menyaksikan performansi Berliner Philharmoniker di Warwick. Namun baru kali ini aku bisa menyaksikan Berliner Philharmoniker di sarangnya, yang dioptimasikannya sendiri buat performa yang maksimal. Cukup memukau, dan membuat tidak bisa bergerak dalam 2 jam performansi tanpa jeda itu. BTW, aku sangat awam dalam musik. Seperti juga sebagian besar masyarakat awam, aku lebih sering memilih sembilan simfoni Beethoven dan beberapa karya yang lebih ringan (piano, konser violin, Wellington, dll). Tapi sua pertama dengan Missa Solemnis dari Berlin Philharmonie ini membuat aku melihat bahwa masih banyak permata indah dari Beethoven yang belum banyak aku jelajahi.
Tapi, sebelum jauh menjelajah, pertama2 … pasang dulu oleh-oleh dari Bayreuth: Lohengrin. Wagner :)







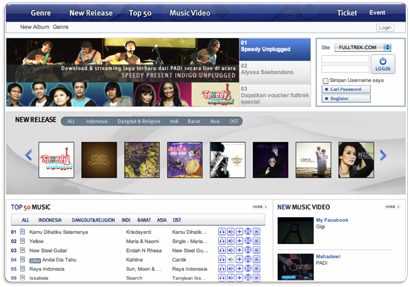



 Memang jadi ada waktunya semua itu dilepas: konsep, komitmen, legenda, visi. Dan biarkan pikiran ini mengaliri segala jalan besar hingga celah sempit yang kita temui hari ini, saat ini, detik ini. Biarkan juga ide-ide jadi frame-frame sporadik yang mencuat ke sana kemari dalam permainan warna yang indah berpola seperti permainan lampu di jalan raya, berpadu dengan percikan air di sungai bersemu coklat dan kenangan yang menarik secara hitam putih ke tenggara dan barat daya. Dan biarkan Debussy menyentak jiwa dengan musik yang pernah dinamai impresionistik itu (entah kenapa).
Memang jadi ada waktunya semua itu dilepas: konsep, komitmen, legenda, visi. Dan biarkan pikiran ini mengaliri segala jalan besar hingga celah sempit yang kita temui hari ini, saat ini, detik ini. Biarkan juga ide-ide jadi frame-frame sporadik yang mencuat ke sana kemari dalam permainan warna yang indah berpola seperti permainan lampu di jalan raya, berpadu dengan percikan air di sungai bersemu coklat dan kenangan yang menarik secara hitam putih ke tenggara dan barat daya. Dan biarkan Debussy menyentak jiwa dengan musik yang pernah dinamai impresionistik itu (entah kenapa).