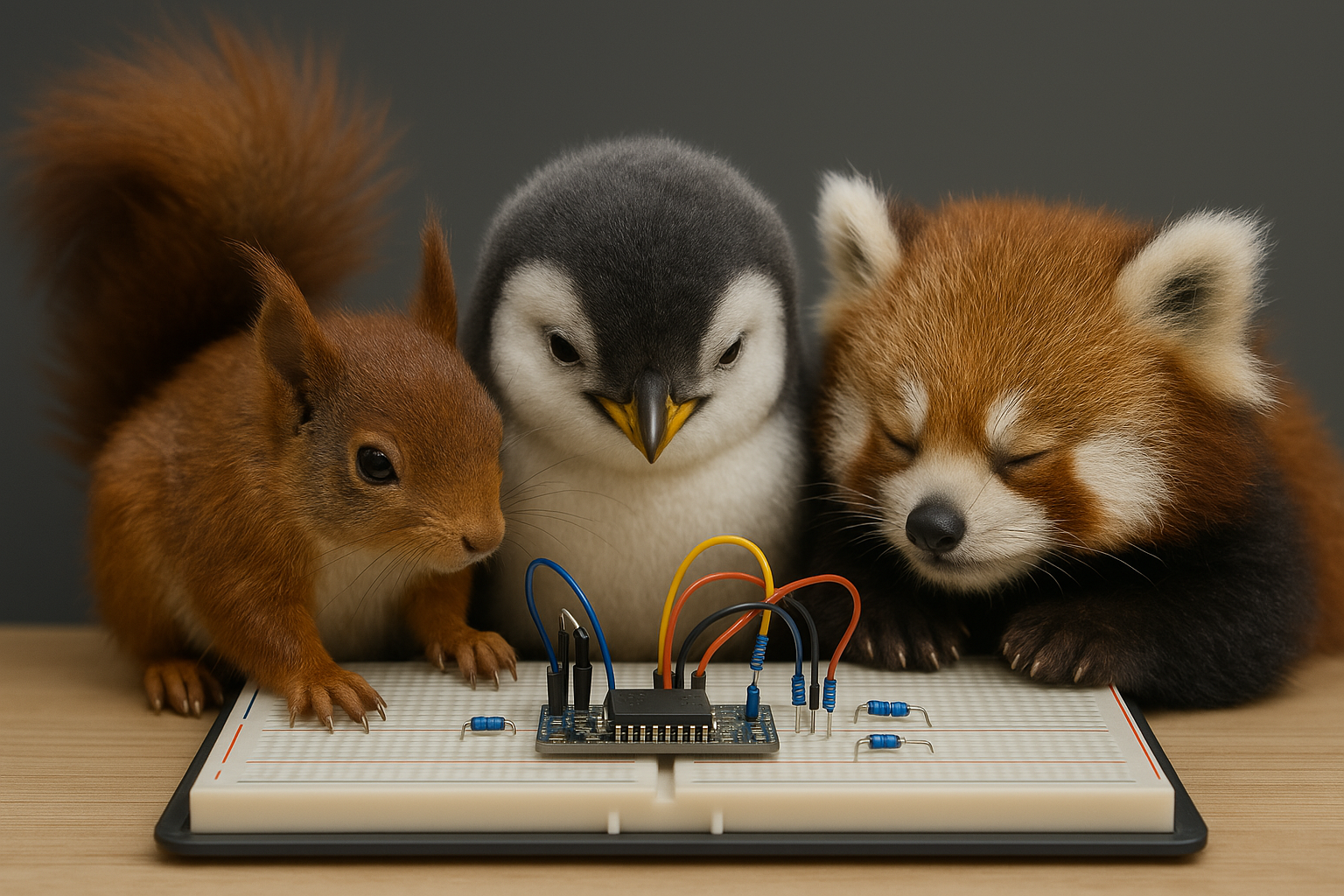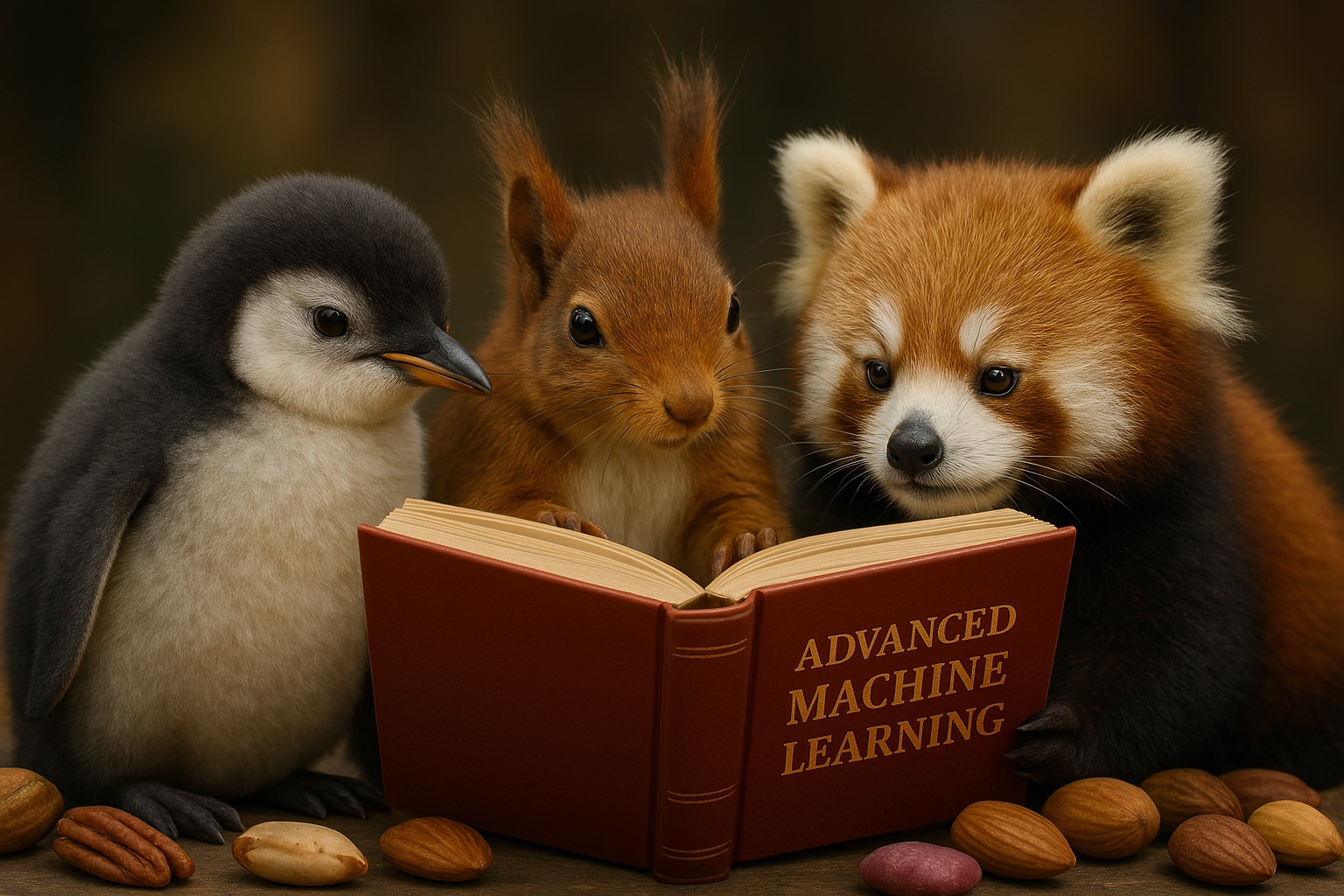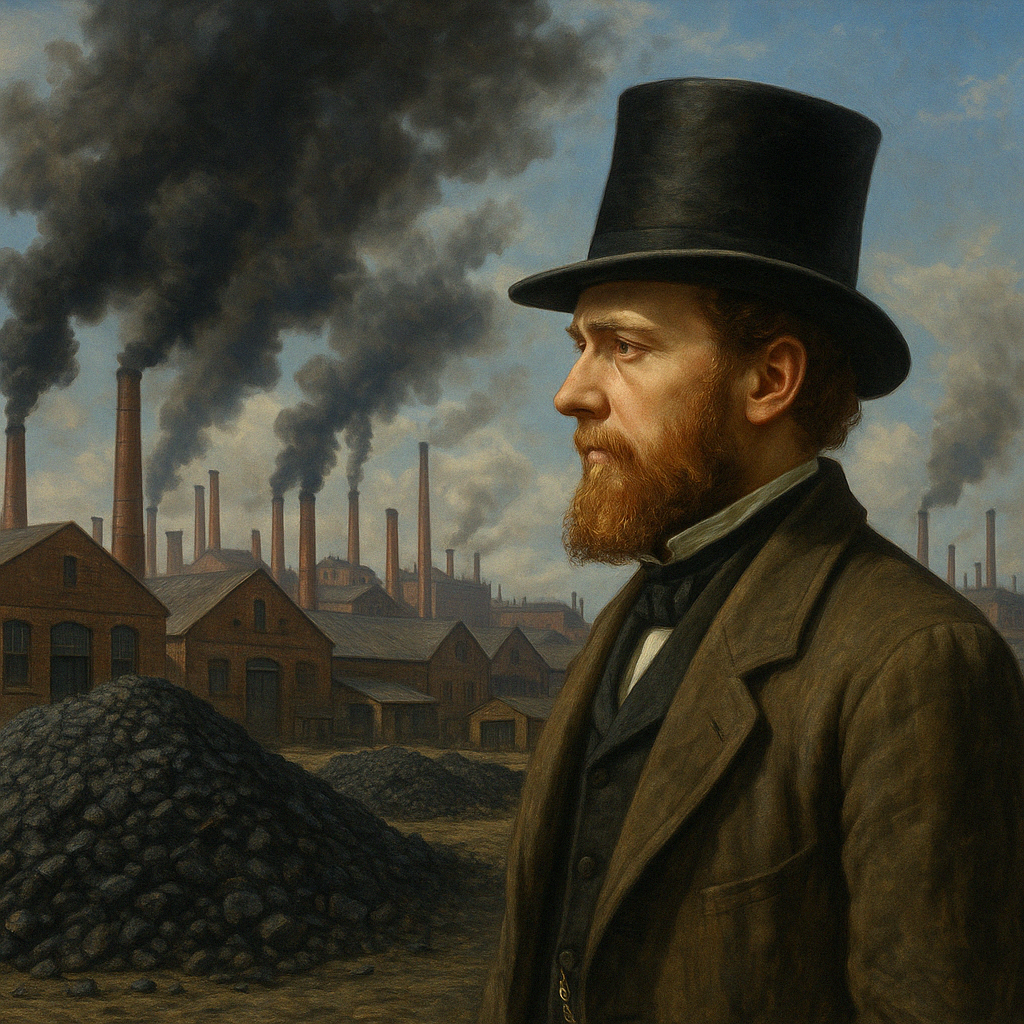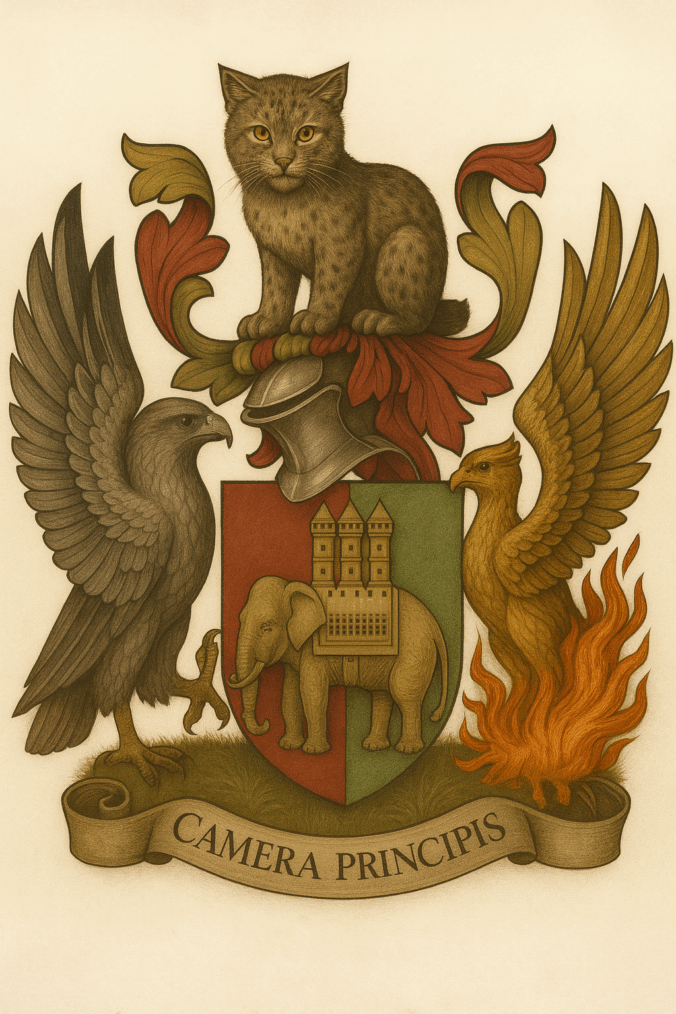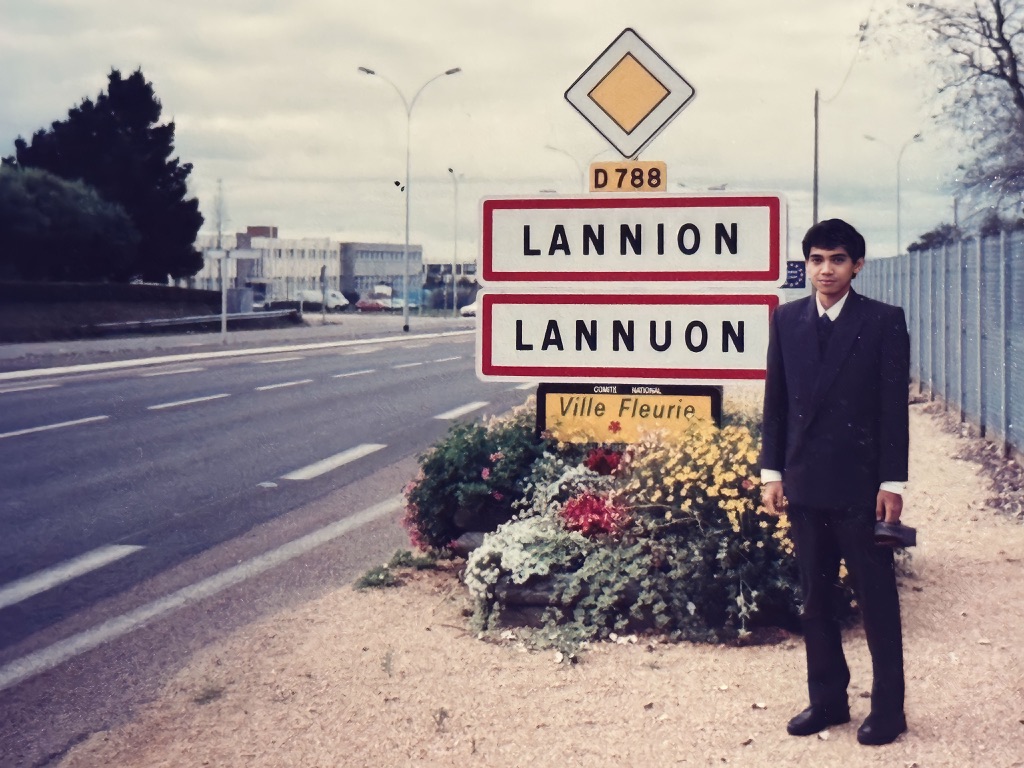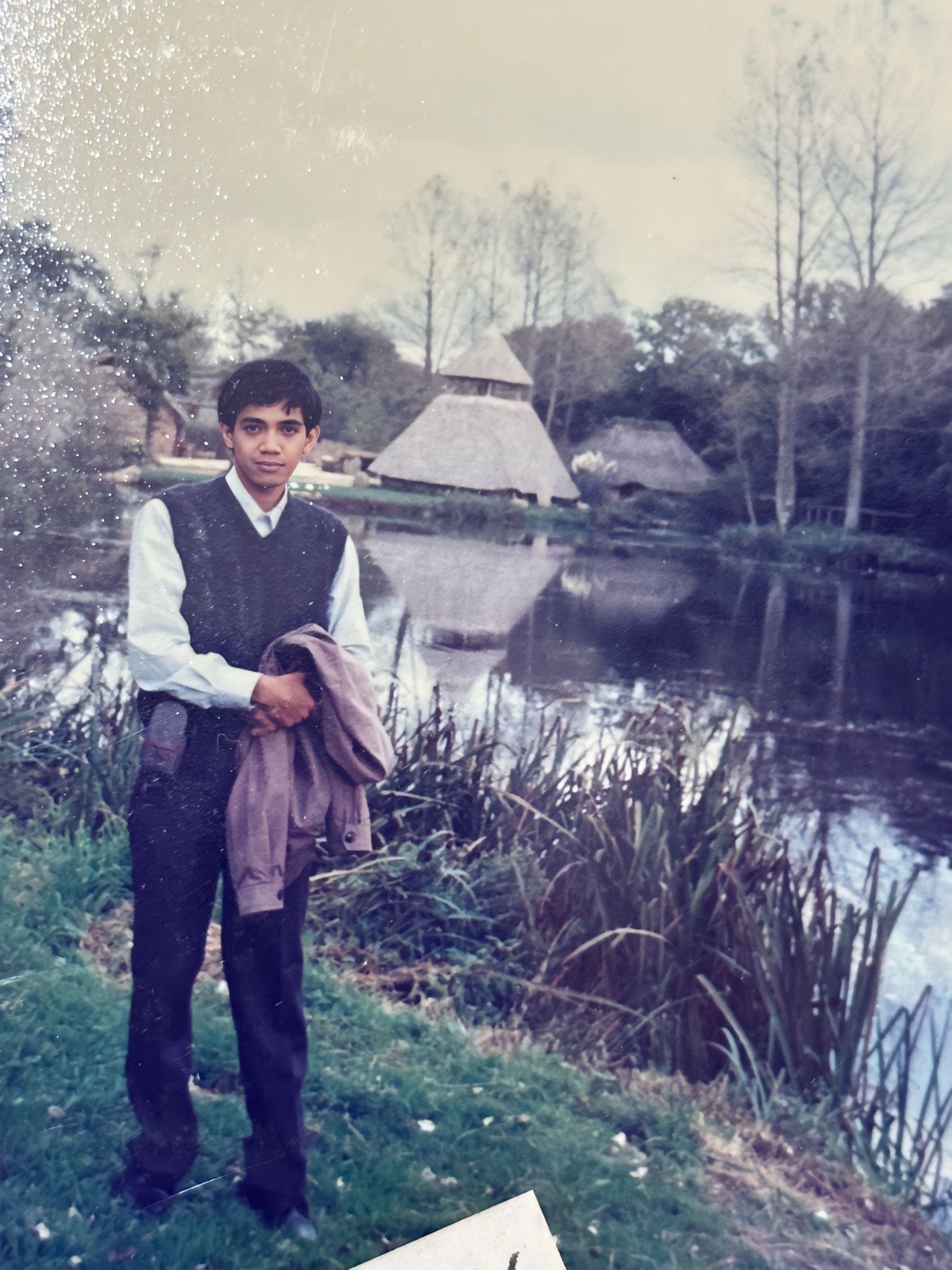Minggu lalu, IEEE Region 10 menyelenggarakan Humanitarian Technology Conference (IEEE HTC) 2025 di Chiba University of Commerce, Jepang, 28 September hingga 1 Oktober, yang mempertemukan para visioner global dengan tema “Beyond SDGs, A New Humanitarian Era with Intelligent Partners.” Konferensi ini berfokus pada sinergi antara intelektualitas manusia dan sistem cerdas yang berkembang dalam meningkatkan dampak kemanusiaan melalui teknologi.

Pada sesi Pembukaan, Presiden IEEE Humanitarian Technologies Board (HTB) Grayson Randall menyampaikan speech yang menekankan peran istimewa para insinyur dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Pesannya menegaskan bahwa insinyur bukan sekadar pemecah masalah, melainkan arsitek harapan yang mampu menjembatani inovasi dengan tanggung jawab sosial. Ia juga memaparkan berbagai peluang baru dalam program-program HT untuk mendorong proyek yang inklusif dan berdampak luas di kawasan Asia-Pasifik. Pada hari kedua, IEEE President-Elect Mary Ellen Randall menyampaikan keynote speech yang visioner tentang roadmap IEEE dalam memajukan profesi rekayasa selaras dengan tujuan pembangunan manusia global. Ia menjelaskan bagaimana arah strategis IEEE, termasuk etika digital dan inovasi berkelanjutan, berfokus pada satu misi utama, peningkatan kualitas hidup manusia melalui kolaborasi yang cerdas.

Hari ke-3 (1 Oktober), aku berpresentasi dalam Special Program 15 dengan judul “Synergy for Sustainable Impact.” Sesi ini dimoderatori oleh Allya Paramitha, dengan para panelis Hidenobu Harasaki, Husain Mahdi, Agnes Irwanti, Bernard Lim, Chie Sato, Saurabh Soni, dan aku sendiri. Diskusi membahas mekanisme kolaboratif antara teknologi, kebijakan, dan inovasi sosial untuk mempercepat hasil kemanusiaan yang berkelanjutan. Aku hampir selalu memulai presentasi tentang sinergi, ekosistem, dan kolaborasi industri dengan menempatkannya dalam framework teori kompleksitas, yang menunjukkan bagaimana sinergi dapat menghasilkan nilai emergence secara non-linear dalam ekosistem kompleksitas. Fenomena emergensi inilah yang menjadi kunci transformasi menuju pencapaian SDG, khususnya dalam memperkuat inklusivitas, ketahanan, dan keadilan.

Aku mengacu pada visi nasional Indonesia, dengan menjelaskan pengembangan ekosistem komersialisasi UMKM sebagai model penerapan teknologi kemanusiaan. Melalui program-program yang meliputi juga pembiayaan mikro, platform digital, dan pemberdayaan koperasi, kita menunjukkan bagaimana teknologi dapat mengangkat pasar yang sebelumnya belum tergarap menjadi sistem yang produktif dan berkelanjutan. Aku juga memaparkan case dimana IEEE Indonesia SIGHT in Sociopreneurship and Sustainability melaksanakan program pengembangan kapasitas bagi Student Branch IEEE Indonesia, yang masing-masing merancang solusi lokal seperti sistem air tenaga surya, pemantauan berbasis IoT, dan inkubasi sosiopreneurship, sebagaimana sedang dijalankan oleh Universitas Gadjah Mada dan Universitas Udayana. Proyek-proyek ini menunjukkan bagaimana keterlibatan berbasis rekayasa dapat berkembang menjadi sociopreneurship yang digerakkan oleh komunitas, dengan menjamin keberlanjutan melalui kepemilikan, replikasi, dan dampak yang terukur.

Pada Hari ke-0 (28 September), aku juga menceritakan versi ringkas program-program ini ke IEEE President-Elect Mary Ellen Randall dan HTB President Grayson Randall. Diskusi ini menjadi landasan bagi pengembangan lebih lanjut program kemanusiaan IEEE di Indonesia dan kawasan Asia-Pasifik, dengan fokus pada ekosistem digital, sosiopreneurship, dan model inovasi berkelanjutan. Program ini juga aku sampaikan dalam Program Khusus 13 (30 September), “From Innovation to Impact: Advancing IEEE Humanitarian Initiatives”, dalam HTA Forum untuk membahas penyelarasan strategis antara kerangka kemanusiaan IEEE dan pengembangan ekosistem regional.

IEEE R10 HTC 2025 ini bukan hanya diskusi antara gagasan, tetapi lebih sebagai aktivitas dinamis dari sinergi, serta perpaduan antara intelektualitas, empati, dan teknologi. Konferensi ini menegaskan bahwa keinsinyuran bukan sekadar tentang mesin atau sistem, melainkan selalu tentang kemanusiaan. IEEE R10 HTC 2025 menjadi tonggak lain dalam perjalanan kolektif untuk membangun dunia yang lebih adil, tangguh, dan berkelanjutan, digerakkan oleh wawasan manusia dan inovasi cerdas.