«Japan Air Lines akan dinyatakan bangkrut» — begitu salah satu headline pagi ini. Dan aku mendadak ingat bahwa Garuda Indonesia pernah mengalami kisah yang sama. Cerita tentang Garuda ini cukup lama, tetapi baru diceritakan kembali beberapa bulan lalu oleh Tanri Abeng. Beliau berkisah bukan sebagai Komisaris Utama Telkom, tetapi sebagai salah satu Management Guru di Telkom. Pasti kisah di bawah ini sudah banyak didengar rekan2 Telkom lainnya.
Di paruh kedua tahun 1990an, Bank Dunia maupun IMF terus mendorong agar pemerintah2 bertindak sebagai regulator, bukan sebagai pemain bisnis. Pemerintah Indonesia mereaksi dengan membentuk departemen yang terpisah antara regulasi dan pengelolaan BUMN. Maka dibentuklah Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN. Tugasnya adalah untuk mengelola BUMN yang saat itu memang kebanyakan salah urus di bawah departemen2 teknis. Tanri Abeng diangkat sebagai Menneg BUMN pertama. Cukup menarik cara Tanri berkisah tentang masuknya ia ke pemerintahan, beberapa kali berdialog dengan Soeharto. Komunikasi canggung ala Soeharto dan para punggawanya membuat Tanri memahami bagaimana Soeharto mengendalikan sistem pemerintahan orde baru di balik layar, hahah. Tapi itu cerita lain. Kita ke Garuda dulu.
 Seperti JAL tahun ini, Garuda masa itu menghadapi ancaman kebangkrutan. Hutang2 jatuh tempo, dan pemerintah tidak dalam kondisi kuat untuk menjadi backup. Kondisi Garuda sendiri memang menyebalkan: banyak benalu, baik dari kalangan cendana, keluarga mantan direksi, maupun pihak lain yang tidak jelas. Tanri merasa bahwa Garuda hanya bisa diselamatkan jika orang mulai menaruh kepercayaan kepada Garuda. Dan itu dimulai dengan menunjukkan bahwa pemerintah serius mengubah sistem yang ada di Garuda. Memberanikan diri datang ke Soeharto, Tanri mohon izin untuk mengganti Dirut Garuda. Lalu ia diam. Zaman orba itu, pejabat ditunjuk atau direstui langsung oleh Soeharto, dan tak pernah diganti kecuali ia bersalah kepada Soeharto. Mengganti pejabat seolah menunjukkan bahwa presiden bisa salah memilih orang, atau tepatnya bahwa presiden bisa salah :). Itu memang zaman kitsch :). Tapi setelah saling diam, Soeharto cuma tersenyum, lalu mengatakan, “Kenapa cuma Dirut? Ganti saja semua direksi.” Satu masalah terpecahkan.
Seperti JAL tahun ini, Garuda masa itu menghadapi ancaman kebangkrutan. Hutang2 jatuh tempo, dan pemerintah tidak dalam kondisi kuat untuk menjadi backup. Kondisi Garuda sendiri memang menyebalkan: banyak benalu, baik dari kalangan cendana, keluarga mantan direksi, maupun pihak lain yang tidak jelas. Tanri merasa bahwa Garuda hanya bisa diselamatkan jika orang mulai menaruh kepercayaan kepada Garuda. Dan itu dimulai dengan menunjukkan bahwa pemerintah serius mengubah sistem yang ada di Garuda. Memberanikan diri datang ke Soeharto, Tanri mohon izin untuk mengganti Dirut Garuda. Lalu ia diam. Zaman orba itu, pejabat ditunjuk atau direstui langsung oleh Soeharto, dan tak pernah diganti kecuali ia bersalah kepada Soeharto. Mengganti pejabat seolah menunjukkan bahwa presiden bisa salah memilih orang, atau tepatnya bahwa presiden bisa salah :). Itu memang zaman kitsch :). Tapi setelah saling diam, Soeharto cuma tersenyum, lalu mengatakan, “Kenapa cuma Dirut? Ganti saja semua direksi.” Satu masalah terpecahkan.
Masalah lain adalah memilih Dirut. Ini keadaan darurat, karena para kreditor besar benar2 sudah mengancam membangkrutkan Garuda. Pada saat seperti ini, yang diperlukan bukanlah profesional di bidang penerbangan. Maka Tanri mendatangi Robby Djohan. Ini adalah tokoh yang pernah membesarkan Bank Niaga (dari nothing menjadi bank swasta kedua terbesar di Indonesia), plus memiliki reputasi yang kuat di kalangan internasional. Dan orang yang tepat memegang sebuah posisi memang adalah orang yang tak memerlukan posisi itu. “Kenapa suruh saya?” balas Robby waktu diminta Tanri, “Saya tidak butuh uang dan pekerjaan.” Tanri menjelaskan bahwa ia memang memerlukan orang yang tidak memerlukan uang. Maka Robby diamanahi menjadi Dirut Garuda.
Robby pun mengundang para kreditor. Pada rapat pertama, ia membuka, “Saya diberi wewenang untuk membantu Anda.” Para kreditor marah. “Yang punya masalah itu Anda. Kami dalam posisi kuat,” kata para kreditor. Robby masih kalem, menjawab, “Kalau negosiasi hari ini tidak berhasil, saya langsung angkat tangan, dan Garuda dibangkrutkan, dan tak ada yang menjamin uang Anda.” Para kreditor langsung paham. Robby mengenang kembali, “Negative networth gila-gilaan, sebab utang (liabilities) jauh lebih besar dibanding harta (asset), sehingga saldonya negatif. Bottom line sudah merah, begitu juga saldo ditahan (retained earning) juga telah negatif.” Ia membacanya seperti seorang bankir: “Kalau kita revaluasi asset sesuai market, maka negative networth akan menjadi kecil. Yang penting, dia noncash-charge, dan negative networth akibat akumulasi kerugian bisa diatasi. Yang perlu dijaga, Garuda tidak boleh rugi, cash flow harus positif. Selain itu, juga harus dijaga posisi serasi antara asset dalam rupiah serta liability dalam dollar AS.” Maka negosiasi intensif untuk penjadwalan hutang dan profitisasi Garuda dimulai. Benalu2 dibersihkan, kepercayaan dibangkitkan, efisiensi ditingkatkan. Pada masa Robby ini juga Kantor Pusat mulai dipindahkan ke wilayah Bandara Soekarno Hatta. Garuda terselamatkan, dan mulai bisa bangkit.
Sayangnya, tak lama Robby di Garuda. Menurut Tanri, memang sengaja Robby tidak dibiarkan lama di sana. Begitu Garuda agak pulih, kendali direksi diserahkan ke pihak lain yang memiliki kesempatan lebih besar untuk melakukan pekerjaan2 detail dan komprehensif. Sementara itu, Robby sendiri diberi pekerjaan baru yang lebih berat: mengawal merger bank2 BUMN menjadi Bank Mandiri.
Catatan: Seluruh kata2 di atas dinarasikan ulang dan tidak dapat dikutip ulang untuk keperluan jurnalistik atau ilmiah.





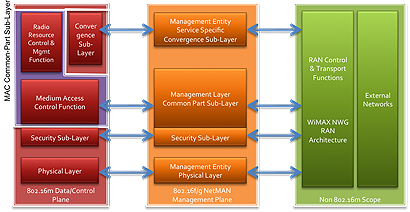







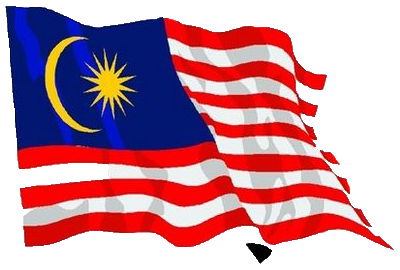

 Apple membuat ‘revolusi’ dengan AppStore, yang ditiru Nokia dengan OVI. Tetapi Acer memanfaatkan kekayaan aplikasi Windows Mobile yang telah dikembangkan para developer bertahun-tahun, mudah dicari dan diinstal, dan dengan forum pemakai yang cukup luas. Lebih dari itu, Acer sendiri mendukung dan mempromosikan content tersegmentasi. Salah satu yang dipaparkan adalah aplikasi lengkap bagi pelaku transaksi saham di IDX. Lokal sekali :).
Apple membuat ‘revolusi’ dengan AppStore, yang ditiru Nokia dengan OVI. Tetapi Acer memanfaatkan kekayaan aplikasi Windows Mobile yang telah dikembangkan para developer bertahun-tahun, mudah dicari dan diinstal, dan dengan forum pemakai yang cukup luas. Lebih dari itu, Acer sendiri mendukung dan mempromosikan content tersegmentasi. Salah satu yang dipaparkan adalah aplikasi lengkap bagi pelaku transaksi saham di IDX. Lokal sekali :).