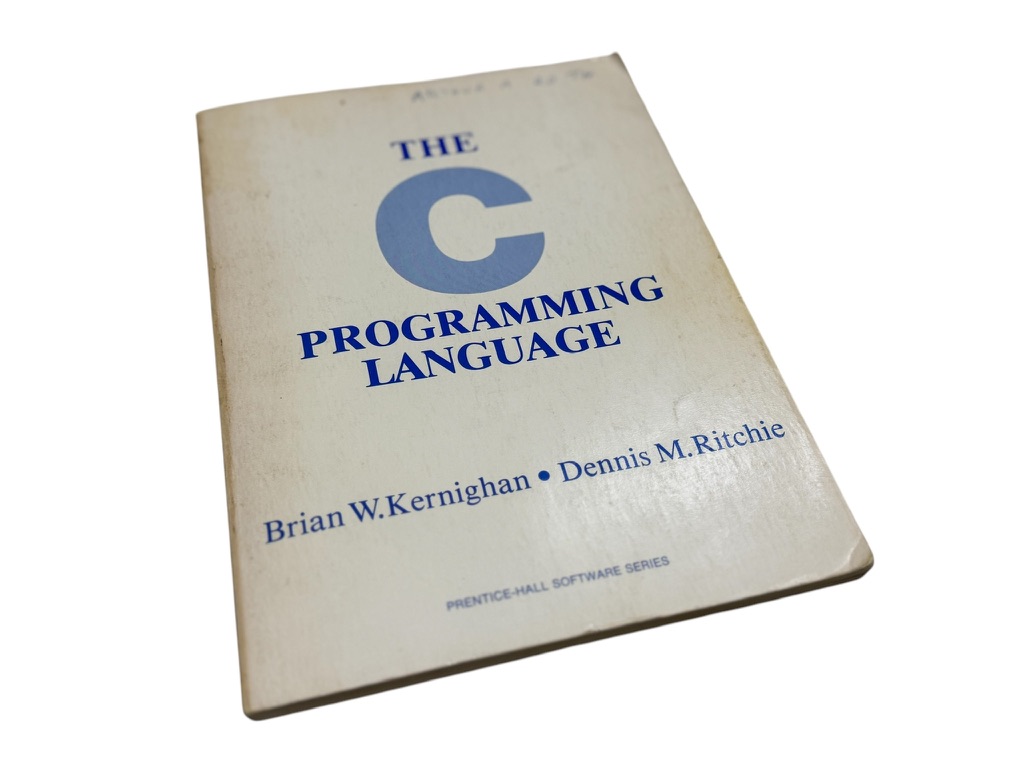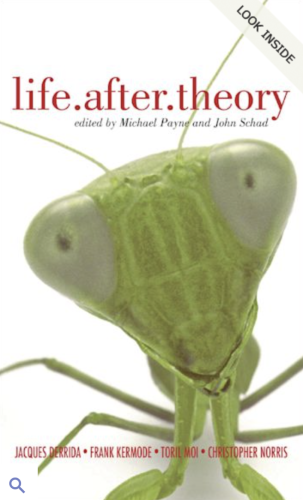Siapa para tokoh di belakang public-key encryption? Orang akan menyebut nama RSA: Rivest, Shamir, Adleman. Atau lebih jauh: Diffie, Hellman, dan Merkle. Tapi beberapa tahun sebelum Diffie, bagian dari dinas rahasia Inggris sudah mengkaji konsep yang serupa. Cheltenham. Nama kota ini mengingatkan ke Ahmad Sofyan yang terus-menerus meyakinkanku bahwa inilah kota tercantik di England. Di sini ada Markas Komunikasi Pemerintah (GCHQ). Di sana John Ellis dulu bekerja, sebagai pegawai yang selalu penuh ide. Separuhnya konyol, dan separuhnya brilian. Sebelum ada kopi instan, ia sudah punya ide mencampur Nescafe dengan gula, dengan alasan efisiensi kerja.
Oh ya, cerita berhenti dulu untuk pesan sponsor. Pagi ini aku minumnya kopi Flores. Jadi agak-agak fly. Kurang banyak kali :).
Sampai mana tadi? Oh ya, di Bell Labs, akhir PD II, ada insinyur iseng membuat catatan bagaimana melakukan scrambling suara analog. Masukkan noise yang banyak dengan noise generator, gitu idenya. Campurkan noise ini ke suara dan kirimkan. Musuh akan menangkap sinyal kita, tetapi tak dapat memisahkan sinyal dari noise. Sementara, lanjut insinyur anonim itu, sekutu di ujung sana, yang punya noise generator yang sama, bisa melakukan pengurangan noise dari sinyal, dan menyisakan sinyal suara yang asli. Sederhana sekali. Tapi tak berguna waktu komunikasi lebih banyak dilakukan secara digital.
Tokoh Ellis kita membaca catatan itu, dan tidak menganggapnya konyol. Dia mulai memikirkan cara agar musuh, biarpun memperoleh sinyal yang sama, dan bahkan mengetahui teknologi enkripsi yang digunakan, tetap kesulitan melakukan dekripsi. Mungkinkah, tanyanya suatu malam. Dan malam itu, di tahun 1969, ia memperoleh jawabannya: bisa! Konsepnya seperti ini, dengan skema Bob mengirim ke Alice tapi diintip Eve. Alice membangkitkan angka yang besar dengan melakukan transformasi matematika dari sebuah bilangan yang dibuatnya. Bilangan yang dibangkitkan dikirimkan ke Bob. Bob mengenkripsi dengan angka yang dikirim Alice. Tapi enkripsi oleh Bob hanya bisa didekripsi oleh bilangan semula yang dibuat Alice. Eve, yang memperoleh baik angka panjang dari Alice mupun data terenkripsi kiriman Bob, tetap tidak bisa melakukan dekripsi. Dia memerlukan angka asli Alice, yang tentu tidak dikirimkan ke mana pun. Bilangan panjang dari Alice boleh dikirimkan melalui jaringan yang tidak aman. Bahkan boleh dipublikasikan :). Dan tetap saja siapa pun akan kesulitan melakukan dekripsi. Ellis menamai skema ini non-secret encryption.
Proyek berlanjut dengan mencari transformasi matematika yang dibutuhkan. Matematikawan Clifford Cocks, yang baru bergabung setelah lulus pascasarjana dari Oxford, memecahkan dalam semalam (juga). Ia melakukannya dengan mengalikan dua bilangan prima yang besar. Mengalikan dua bilangan prima yang besar itu relatif mudah. Yang jauh lebih sulit adalah menguraikan hasil kalinya menjadi dua faktor prima yang benar. Ia menyampaikan laporannya ke mentornya, Nick Patterson, sesama matematikawan. Patterson langsung berteriak di depan pintu: “Ini penemuan kriptografis terbesar sepanjang sejarah!”
Tapi tentu, ini adalah lembaga birokratik, seperti juga agen rahasia di mana pun. Hasil penemuan tersimpan di bawah selimut. Memberikan ruang kepada Diffie cs untuk menemukan kembali penemuan Ellis, dan RSA untuk menemukan kembali pememuan Cocks. Dan seterusnya sampai Zimmerman, PGP, GPG, GPP, EGP, dan semacamnya. Buat yang tidak pernah membaca soal ini, yang GPP dan EGP itu bohong. Tapi kita harus tahu: skema semacam inilah yang kini memungkinkan e-commerce berkembang di Internet.
Ada waktunya rahasia tentang Ellis ini dibocorkan ke Diffie. Whitfield Diffie yang terperanjat ingin menemui tokoh ini. Pertemuan itu terlaksana tahun 1982 di Cheltenham.
“Gimana rasanya menemukan non-secret encryption?” tanya Diffie.
“Siapa bilang?” sahut Ellis.
Diffie menyebutkan nama seorang tokoh NSA.
“Kamu kerja untuk dia?” tanya Ellis.
Percakapan mereka bersahabat, tapi Ellis enggan membahas soal enkripsi :). Ia kemudian hanya menyentil sekali, dengan mengatakan “You did more with it than we did,” lalu meneruskan kerahasiaannya. Cerita lebih lanjut, baca aja buku Crypto.







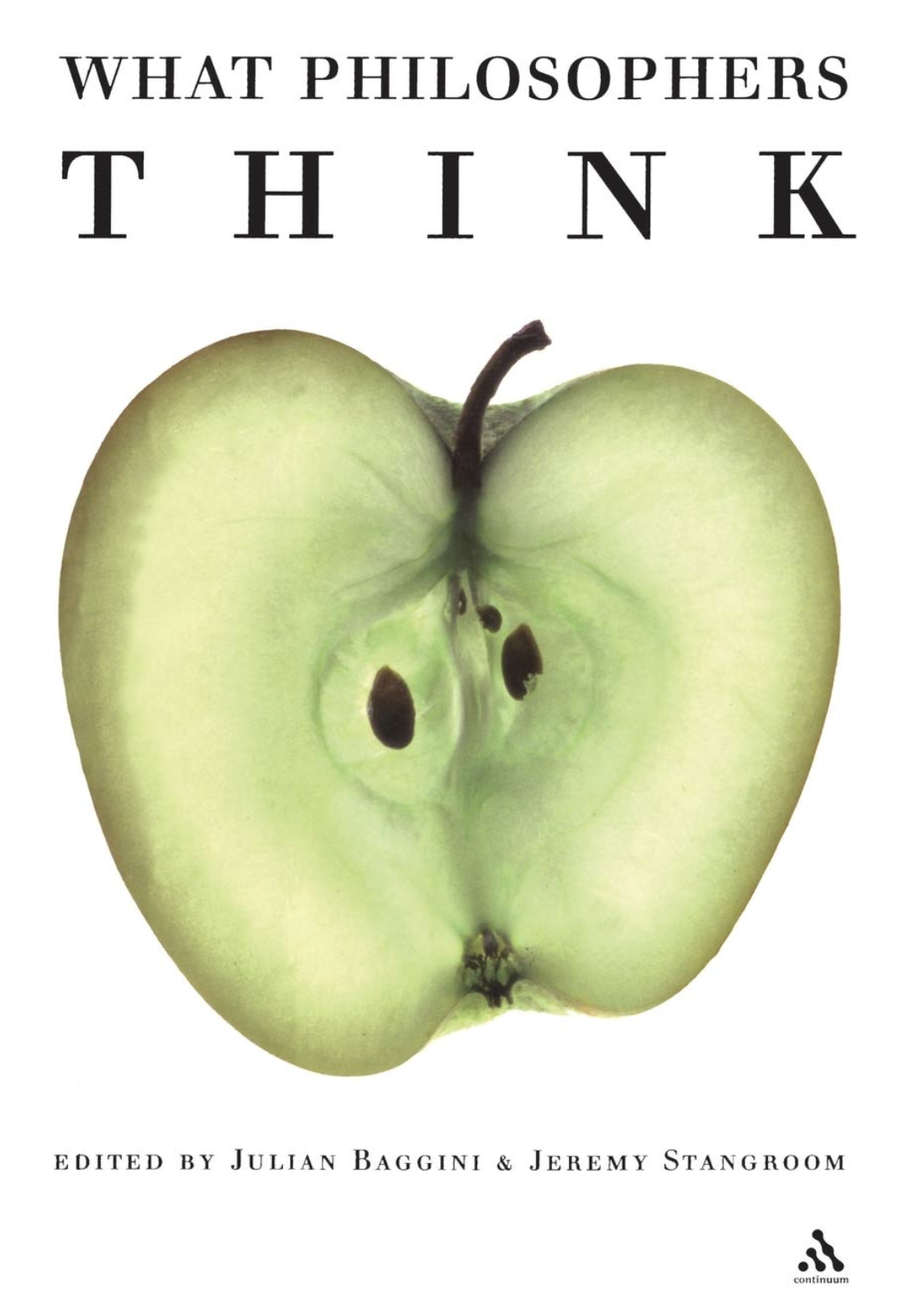

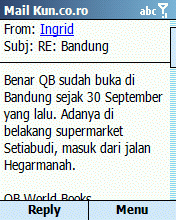 Ketemu juga aku sama satu lagi titik lemahku. Udah tahu bulan kemaren ini beli buku kebanyakan, bulan ini masih nggak bisa menahan diri juga. Kalau judulnya bookaholic sih, kali2 nggak pa-pa, bisa ngaku2 intelek. Tapi kalau judulnya cuman book shopaholic? Malu2in aja :). Salah satu pelarian dari tekanan yang nggak/belum bisa dilepas kali yach.
Ketemu juga aku sama satu lagi titik lemahku. Udah tahu bulan kemaren ini beli buku kebanyakan, bulan ini masih nggak bisa menahan diri juga. Kalau judulnya bookaholic sih, kali2 nggak pa-pa, bisa ngaku2 intelek. Tapi kalau judulnya cuman book shopaholic? Malu2in aja :). Salah satu pelarian dari tekanan yang nggak/belum bisa dilepas kali yach.