Abad lalu, AS adalah puncak kekuatan industri. Dengan kapasitas industri dan inovasi terdepan, AS berproduksi dalam skala besar sambil menciptakan kelas menengah yang luas. Namun, sejak akhir abad ke-20, dominasi ini terkikis. Perusahaan Amerika seperti Apple dan Microsoft sukses secara global, tapi industri AS mulai melamah. Ini sebuah paradoks menarik: strateginya menang, tetapi negara kalah.
AS memimpin liberalisasi dan globalisasi, dengan memaksakan perdagangan bebas, deregulasi, dan offshoring sebagai strategi pertumbuhan ekonomi dan keunggulan kompetitif. Hal ini diperkuat masa Reagan-Thatcher dan dilembagakan dalam bentuk NAFTA dan dukungan atas keanggotaan RRC di WTO. Manufaktur padat karya dialihkan ke negara berbiaya rendah, sementara AS berfokus ke layanan bernilai tinggi dan inovatif, sambil menikmati manfaat efisiensi global.
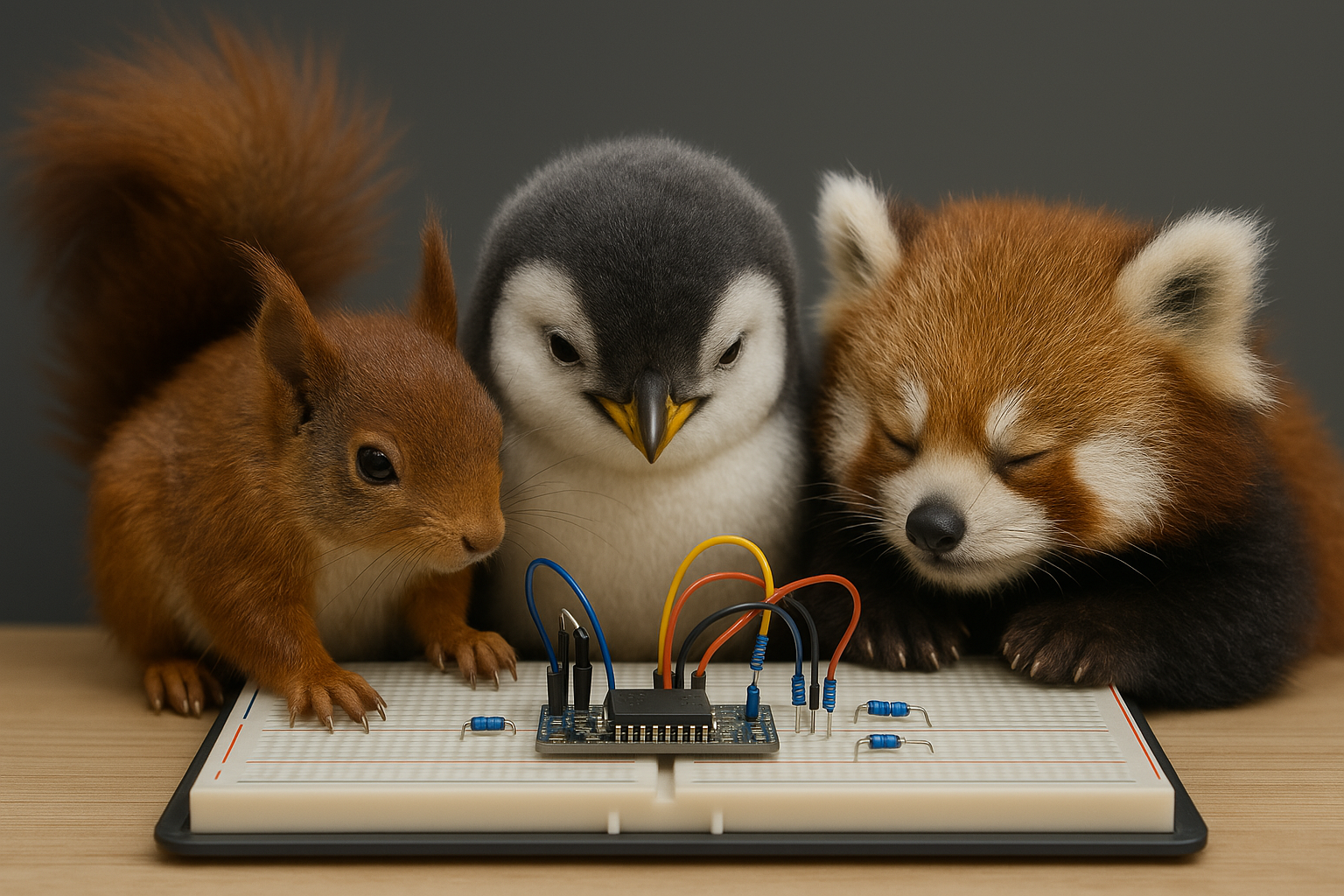
Di level perusahaan, cara kerja ini efektif. Apple membangun salah satu ekosistem paling bernilai di dunia, dengan integrasi erat antara desain, software, layanan, dan hardware. Hampir semua hardware diproduksi dan dirakit di luar negeri, terutama RRC. Microsoft mendominasi perangkat lunak dan layanan enterprise, tetapi ekosistem globalnya—cloud, pengembangan sistem, dan rantai pasok—makin bergantung pada infrastruktur dan stabilitas politik internasional.
Makin jelas bahwa strategi berbasis ekosistem ini—meskipun brilian dalam skalabilitas, penguasaan pasar, dan profitabilitas—pada dasarnya rapuh. Strategi ini dibangun atas asumsi lingkungan global yang stabil, arus tenaga kerja lintas batas, modal, dan data yang tak terganggu, serta konsensus geopolitik yang kini mulai runtuh. Pandemi COVID-19, perang teknologi AS–China, dan meningkatnya kebijakan proteksionis di seluruh dunia menunjukkan rapuhnya mata rantai pasok dan ketergantungan atas platform tersebut.
Model kapitalisme AS juga dangkal dan berorientasi jangka pendek. Perusahaan didorong memaksimalkan laba triwulanan dan nilai return, dan jarang berfokus pada berinvestasi pengembangan kapabilitas secara domestik. Serikat pekerja melemah, dan infrastruktur politik dan sosial yang didukung kelas pekerja ikut runtuh. Pergeseran budaya menuju “knowledge economy” diikuti gagasan bahwa produksi fisik kurang berharga daripada platform digital, kekayaan intelektual, dan rekayasa keuangan.
Inti kelemahan terletak pada optimisasi efisiensi secara berlebihan dengan mengorbankan resiliansi. Dengan mengalihkan manufaktur penting ke luar negeri, AS kehilangan pekerjaan, juga pengetahuan industri, infrastruktur logistik, dan kemampuan merekonfigurasi produksi domestik secara cepat saat krisis melanda. Hal ini tampak pada krisis semikonduktor, APD, dan kebutuhan pokok lainnya selama pandemi awal dekade ini.
Ideologi dangkal ini juga diperluas ke Inggris, yang setia mengikuti strategi liberalisasi ekonomi AS. Di bawah kepemimpinan buruk Thatcher tahun 1980-an, Inggris melakukan swastanisasi industri besar, deregulasi sektor keuangan, pelemahan serikat buruh, dan self-positioning sebagai pusat global untuk layanan—terutama layanan keuangan. Seperti AS, Inggris membiarkan basis manufakturnya menyusut demi layanan bernilai tinggi yang terkonsentrasi di Tenggara, terutama London.
Tidak seperti AS, Inggris masih kurang di sisi skalabilitas, keragaman sumber daya, dan dominasi teknologi global. Inggris jadi mudah runtuh akibat ketimpangan regional yang mencolok, produktivitas yang menurun, dan kekurangan investasi kronis dalam infrastruktur dan pendidikan. Brexit, dalam banyak hal, merupakan ekspresi politik dari keterasingan ekonomi ini—pemberontakan terhadap globalisasi, sentralisasi, dan persepsi bahwa rakyat telah ditinggalkan oleh pengambil keputusan.
Di kedua negara, kita melihat kontradiksi inti: perusahaan menang secara global, namun ekonomi nasional menderita karena kerapuhan, ketimpangan, dan hilangnya kedaulatan di sektor-sektor strategis utama. Strategi berbasis ekosistem dari perusahaan seperti Apple dan Microsoft terus menghasilkan nilai yang besar, tetapi dikembangkan di atas geopolitik yang rapuh, tenaga kerja berbiaya rendah di luar negeri, dan jaringan logistik kompleks yang semakin rentan terhadap gangguan.

Ekosistem bisnis konon merupakan metafora dari ekosistem alam, yang berkembang melalui keragaman, redundansi, dan dukungan timbal balik. Tapi ekosistem bisnis yang dibangun oleh raksasa teknologi kadang justru kehilangan aspek semacam ini. Mereka cenderung bergerak ke sentralisasi, dominasi, dan efisiensi, membuatnya lebih menyerupai monokultur industri daripada ekosistem sejati. Ketika tekanan datang—dalam bentuk sanksi, pandemi, atau perang dagang—sistem-sistem ini tidak bergerak adaptif dan elastis, tapi justru patah.
Bukan berarti model ekosistem ini cacat secara mendasar. Model ini tetap menjadi salah satu kerangka kerja paling kuat untuk penciptaan nilai dalam ekonomi jaringan. Namun perlu ada (r)evolusi. Perusahaan harus membangun ekosistem yang efisien, namun sekaligus tetapi juga tangguh dan adaptif di level ekosistem (bukan di level perusahaan). Perlu dilakukan diversifikasi rantai pasok, investasi dalam kapabilitas lokal, dukungan atas kesehatan ekosistem, serta mitigasi atas risiko politik dan lingkungan.
Negara juga harus meninjau ulang cara kerjanya. Kembali ke proteksionisme bukanlah jawabannya, tetapi kembali ke liberalisme pasar juga salah. Sektor-sektor strategis harus dibangun kembali atau didukung secara domestik tidak hanya demi daya saing ekonomi, tetapi juga untuk ketahanan nasional. Kebijakan harus mendorong investasi jangka panjang, regenerasi regional, dan kebijakan industri yang selaras dengan inovasi.
Penerapan strategi berbasis ekosistem tidak boleh terlalu sempit dan dangkal. Perlu pandangan jauh ke depan, dan perlu perhatian besar terhadap kesehatan ekosistem ini sendiri. AS dan Inggris memberikan pelajaran bagi negara mana pun, bahwa ketahanan, kedaulatan ekonomi, dan kemakmuran inklusif akan sama pentingnya dengan efisiensi dan inovasi.


Leave a Reply